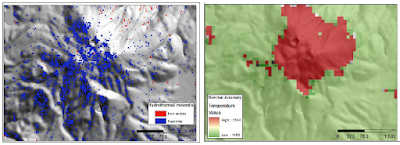Lingkungan Pengendapan Transisi dan Laut : Sistem
Pulau Penghalang
(Barrier island)
ABSTRAK
Sedimen
diendapkan pada beberapa lingkungan pengendapan. Sedimen terendapkan pada
lingkungan darat, transisi dan laut. Sistem pulau penghalang atau sering
disebut barrier island merupakan
salah satu sistem pada lingkungan pengendapan transisi dan laut. Barrier island merupakan tumpukan
sedimen hasil gelombang dan proses angin. Terendapkan dipengaruhi oleh arus
tidal. Barrier island biasanya
terendapkan secara bertahap maupun langsung. Barrier terpisah dengan
mainland(daratan). Barrier island mempunyai luas berkisar kurang dari 100m.
Pada umumnya barrier island akan luas ketika supplai sedimen sangat berlimpah
dan relatif sempit ketika erosi tinggi. Panjangnya tidak hanya dipengaruhi oleh
banyak suplai sedimen tetapi juga oleh gelombang dan arus tidal dari laut.
Barrier island merupakan gabungan
dari tiga lingkungan yang berbeda. Ketiganya adalah subtidal-subaerial barrier-beachcomplex. Biasanya dibelakang
barrier island terdapat estuari, lagoon, atau marsh. Barrier island ditemukan
dibelahan dunia manapun kecuali antartika.
SISTEM PULAU
PENGHALANG (BARRIER ISLAND)
Sistem
pulau penghalang (barrier island) terbentuk pada relief pesisir yang rendah,
dan continental shelves nya dapat
menyediakan tempat untuk mengendapkan sedimen. Selain itu, ketika air pasang,
sedimen dapat diendapkan menuju ke darat. Pada umumnya barrier terdapat pada 3
zona yaitu : beach, barrier interior, dan
the landward margin. Daratan-pantai dan sistem pulau penghalang merupakan
kumpulan sedimen yang lengkap. Bentuknya memanjang sebagai hasil pengendapan
yang sejajar dengan garis pantai. Berbeda dengan sistem pengendapan lain
seperti estuarine, bay, yang sifatnya memotong garis pantai. Sedimen yang dominan
pada lingkungan pengendapan ini adalah pasir. Pasir pada sistem ini sangat
tebal. Ketebalannya dapat mencapai 10-20 m (Reineck
and Singh, 1980). Ketika barrier island terbentuk dan terendapkan, maka sedimen
akan tergradasi dari darat hingga back barrier.
Beach deposits
Gambar 1. Beach
hingga offshore(sumber : Encyclopedia of
sediments and sedimentary rocks by Gerald V Midleton)
Beach deposits terbentuk pada
muka pantai atau foreshore yang
merupakan intertidal zone. Memanjang
dari arus pasang yang rendah ke arus pasang yang tinggi yang dipengaruhi oleh
gelombang. Sedimen pada foreshore biasanya didominasi oleh sedimen halus ke
pasir sedang tetapi ada juga hamburan kerikil dan kerakal. Struktur sedimen
yang terbentuk adalah laminasi yang dibentuk oleh arus yang datang dan arus
balik. Tipis, dan mineral berat kadang kadang muncul. Mungkin akan terbentuk
dune hingga antidune pada saat arus balik (backwash).
Shoreface deposits
Shoreface
terbentuk pada lingkungan yang memanjang pengaruh arus yang lemah pada pantai
hingga dasar gelombang yang terendah. Dasar gelombang merupakan kedalaman
gelombang yang mendekati dasar laut. Kedalaman dasar gelombang pada shoreface
biasanya sekitar 10-15 m, namun kedalaman ini dapat berubah secara signifikan
ketika terjadi badai. Upper shoreface deposits terbentuk pada lingkungan
yang didominasi oleh arus gelombang yang kuat dan arus sepanjang pantai
(longshore currents). Struktur sedimen yang terbentuk adalah cross-bed. Ada
juga terdapat trace fosil seperti skolithos
namun tidak melimpah. Middle shoreface terbentuk dibawah kondisi energi
yang tinggi yang dapat menghancurkan gelombang berasosiasi dengan longshore and rip currents. Sedimen yang
terendapkan pasir halus-pasir sedang dengan silt yang minoritas. Lower
shoreface terbentuk pada kondisi energi
yang relatif rendah. Mengandung pasir – pasir yang sangat halus namun mungkin
mengandung silt and clay. Struktur sedimen yang terbentuk adalah perlapisan
silang siur, planar stratification dll.
Back barrier
Back barrier terendapkan pada daratan barrier beaches. Terbentuk pada saat
badai membawa gelombang dan memotong penghalang (barrier). Didominasi oleh
butiran sedimen pasir yang berukuran halus hingga medium. Struktur sedimen yang
terbentuk adalah laminasi planar dalam skala yang kecil hingga besar.
Gambar
2. Teori pembentukan Pulau penghalang (barrier
island) (sumber : Encyclopedia of
sediments and sedimentary rocks by Gerald V Midleton)
Pembentukan
barrier island
Ada tiga teori
yang membahas tentang pembentukan barrier island (pulau penghalang) yaitu
:
1.
Offshore Bar
accretion
oleh de Beamount, 1854
2.
Spit Accretion
and breaching oleh
Gilbert, 1885
3.
Mainland
Detachment
oleh Hoyt, 1967
Ketiga
teori ini muncul dengan keunikannya. Sekarang mari kita bahas ketiganya.
1.
Offshore Bar Accretion (de Beamount, pada tahun 1854)
Menurut
de Beamount, gelombang dari laut membawa sedimen yang dari laut ke offshore secara bertahap. Pada awalnya
gelombang membawa sedikit sedimen, setelah itu gelombang yang lain membawa
sedikit sedimen lain. Hingga akhirnya banyak sedimen yang terendapkan pada
offshore hingga nantinya menjadi barrier island. Namun teori ini tidak disepakati
karena pada daerah offshore bisa saja terjadi arus balik yang dapat
menghancurkan sedimen yang sudah diendapkan sebelumnya. Sehingga kecil
kemungkinan terendapkan sedimen menjadi pulau penghalang (barrier island).
2.
Spit Accretion and braeching
Menurut
Gilbert, 1885 pulau penghalang terbentuk karena terbentuknya spit pertama kali.
Spit itu mengalami hancuran (breaching) oleh badai gelombang sehingga terbentuk
pulau penghalang.
3.
Maindland datachment
Teori
ini dikemukakan oleh hoyt pada tahun 1967. Ia berpendapat bahwa pulau
penghalang (barrier island) terbentuk
oleh pengarus sea level yang
naik-turun. Pada saat sea level turun, maka akan terendapkan sedimen setelah
itu pada saat sea level kembali naik, maka otomatis akan mengendapkan sedimen
yang lebih tinggi lagi. Hal ini marupakan kronologi pembentukan pulau
penghalang (barrier island).
Tipe
Morfologi Barrier Island
Bentuk barrier,
stabilitas, dan proses erosional atau pengendapannya sangat dipengaruhi oleh
suplai sedimen, kenaikan sea level, dan juga topografi dari daratannya. Ada dua
tipe bentukan barrier yaitu :
1.
Prograding
Barriier
yang terbentuk pada saat menuju ke darat (seaward direction). Prograding
terbentuk dengan suplai sedimen yang melimpah pada saat periode yang stabil
atau pada saat sea level naik dengan
lambat. Pasir ini berasal dari offshore
sources. Contohnya Provinceland spit pada utara Cape Cod.
Gambar
3. Progradation (sumber : Encyclopedia of
sediments and sedimentary rocks by Gerald V Midleton)
1.
Retrograding
Pada
saat suplai pasir yang tidak mencukupi untuk bolak balik dengan sea level yang
naik. Menurut Moslow dan Colquhoun (1981) pasokan sedimen yang tidak cukup
membentuk retrogradational. Ketika
jumlah pasir yang berkontribusi terhadap barrier sedikit maka pasir akan
tertransportasi dari barrier. Pasir akan hilang pada saat badai, tertransport
pada saat erosional dll.
Gambar
4. Retrogradational (sumber : Encyclopedia
of sediments and sedimentary rocks by Gerald V Midleton)
Stratigrafi pulau penghalang (Barrier Island)
Barrier memperlihatkan
variasi bentukan dengan tipe sedimen yang berbeda. Stratigrafi barrier terdiri
dari butiran, mineral, dan banyak yang mencirikan sebuah endapan barrier. Beberapa hal yang mempengaruhi
hal itu adalah suplai sedimen, kenaikan sea
level, energi gelombang dan arus, iklim, dan topografi daratan pada saat barrier berkembang menjadi sebuah
endapan stratigrafi. Faktor lain yang mempengaruhi ketebalan barrier adalah akomodasi wadah yang
tersedia untuk mengakumulasi sedimen pada barrier.
Sekuen
stratigrafi barrier biasanya
mengandung endapan cerukan tidal, khususnya barrier
yang memanjang di pesisir dimana tidal
inlets (cerukan tidal) terbuka dan tertutup. Karena pada daerah ini
merupakan daerah yang aktif. Ada istilah yang disebut up drift dan down drift.
Updrift adalah pada saat barrier memanjang (elongates) sedangkan downdrift
adalah pada saat barrier menurun (retreats).
Tipe
morfosedimen barrier prograding
memiliki tipikal reggresive stratigraphy
karena tipe ini terbentuk pada arah arus yang menuju ke daratan ketebalan barrier nya sekitar 10-20 m biasanya
mengandung butiran pasir yang halus dan lanau (silt). Urutan barier terdiri dari pasir nearshore,
endapan pantai, dan pasir dune yang terbentuk. Terbentuk juga struktur coarsening up ward . Sedangkan tipe
morfosedimen barrier retrograding
terbentuk berlawanan dengan prograding,
sehingga bertipikal transgresive
stratigraphy . Jika barrier turun
cukup jauh dari landward (daratan)
maka terendapkan pada dasar sekuen. Pada keadaan ini kita dapat menemukan akar
pohon, tanah, dan endapan yang lainnya tak terkecuali silt dan clay. Disekitar
cerukan tidal akan ditemukan channel dan
floodtidal delta sands. Pada banyak
kasus, barrier dipengaruhi oleh dua
faktor yaitu seaward dan landward. Hal ini dapat terjadi karena
suplai sedimen dan ketinggian dari naiknya sea
level. Contohnya suatu sekuen sedimen barrier
yang jarang hanya terendapkan dune, lagoonal deposits dll tetapi tidak
seperti endapan yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Gambar
5. Transgresion dan Regresion
Kesimpulan
-
Barrier island
terbentuk di lingkungan transisi
-
Pembentukan
barrier island ada 3 toeri yaitu :
1.
Offshore Bar
accretion
oleh de Beamount, 1854
2.
Spit Accretion
and breaching oleh
Gilbert, 1885
3.
Mainland
Detachment
oleh Hoyt, 1967
Namun
pada akhirnya ketiga ini dapat terbentuk sesuai dengan kondisi di tepat yang
sebenarnya
-
Di
setiap pulau penghalang (barrier island) terbentuk dengan proses yang berbeda –
beda
-
Beberapa
hal yang mempengaruhi variasi barrier
island adalah suplai sedimen, kenaikan sea
level, energi gelombang dan arus, iklim, dan topografi daratan pada saat barrier berkembang menjadi sebuah
endapan stratigrafi.
-
Ada
2 tipe morfosedimen barrier island
yaitu prograding dan retrograding
DAFTAR PUSTAKA
Boggs Sam, 2006 Principle of Sedimentary and Stratigraphy
New Jersey : Prentice Hall
Midleton V
Gerald, 2003 Encyclopedia of sediments and sedimentary rocks Canada : Springer
Surjono S Sugeng
, 2009 Sedimentologi Yogyakarta : Jurusan Teknik Gologi FT UGM